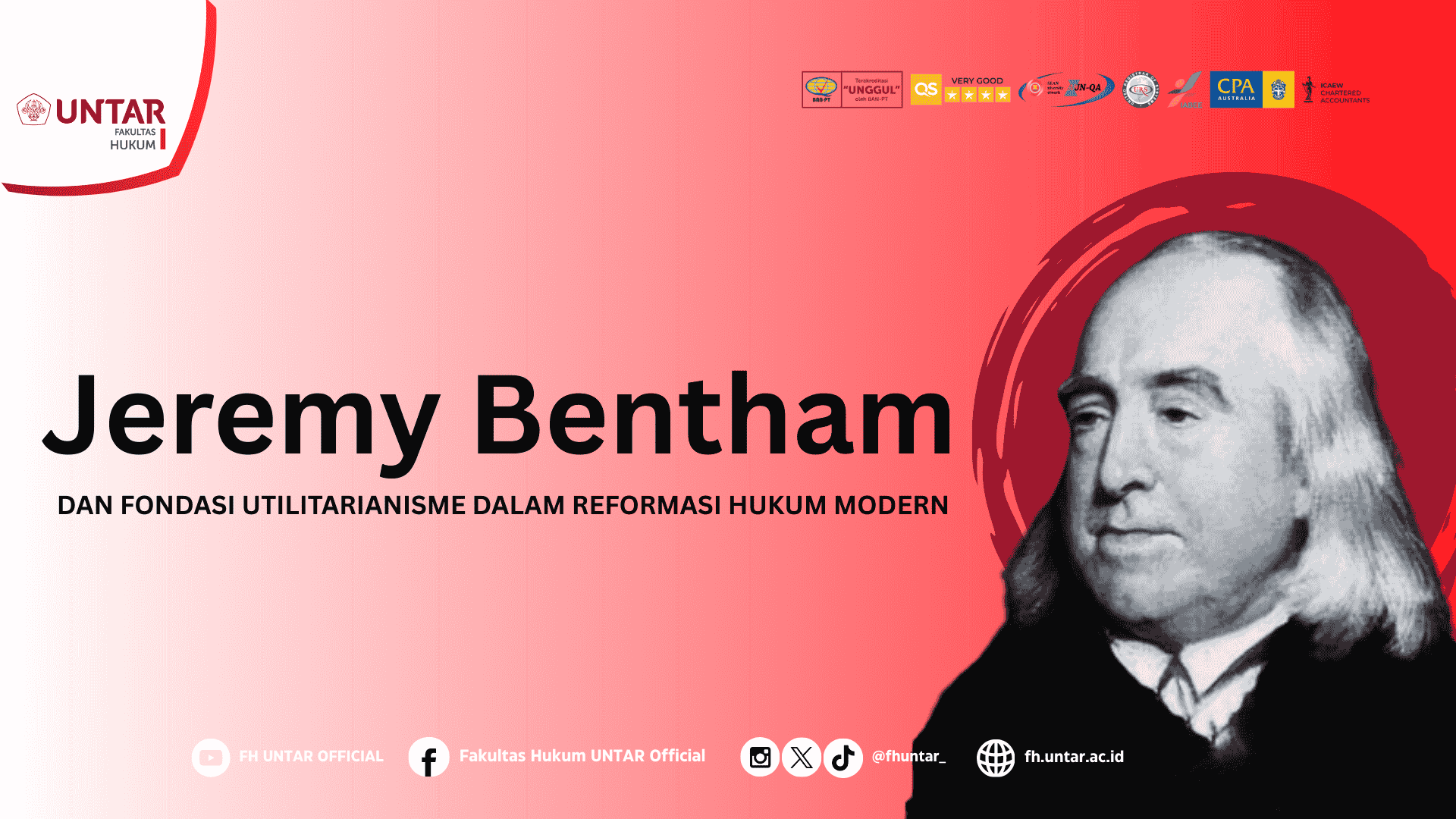Jeremy Bentham (1748–1832) merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran hukum dan filsafat moral modern. Sebagai seorang filsuf, ahli hukum, dan reformis sosial asal Inggris, Bentham dikenal luas sebagai pelopor utama dari teori utilitarianisme, suatu pendekatan normatif yang menempatkan prinsip manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness of the greatest number) sebagai tolok ukur utama dalam menilai baik buruknya suatu tindakan atau kebijakan hukum.
Dalam bidang hukum, Bentham juga menolak pandangan tradisional yang memandang hukum sebagai manifestasi kehendak ilahi atau norma-norma moral alamiah yang bersifat tetap. Sebaliknya, Bentham memandang hukum sebagai konstruksi manusia yang bersifat instrumental, yang keberadaannya harus senantiasa diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, bagi Bentham, tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, bukan semata-mata menegakkan keadilan dalam arti abstrak.
Konsepsi hukum menurut Bentham berlandaskan oleh apa yang disebut sebagai prinsip utilitas (principle of utility). Pada prinsip ini menganjurkan bahwa suatu norma hukum dikatakan baik atau sah apabila norma tersebut mendatangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya, terutama dalam konteks dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam karya utamanya, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), Bentham bahkan mengembangkan sebuah metode yang dikenal sebagai kalkulus hedonistik (hedonic calculus) untuk menghitung intensitas, durasi, kepastian, dan luasan dampak kebahagiaan atau penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau kebijakan hukum.
Salah satu kontribusi Bentham yang signifikan dalam pengembangan hukum modern adalah seruannya untuk kodifikasi hukum. Ia menentang keras sistem common law Inggris yang menurutnya tidak rasional, bersifat kabur, serta sulit diakses oleh masyarakat awam. Bentham mengusulkan agar hukum dikodifikasi secara sistematis dan dirumuskan dalam bahasa yang jelas, sehingga dapat dipahami dan diterapkan secara adil oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan ketertiban dan kebahagiaan publik.
Selain itu, Bentham juga dikenal karena kritiknya terhadap doktrin hak asasi manusia alamiah. Ia menolak gagasan bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir secara alami dan menyebut konsep tersebut sebagai “nonsense upon stilts” (omong kosong yang dibesar-besarkan). Bagi Bentham, hak hanya sah dan dapat ditegakkan apabila dilembagakan dalam sistem hukum positif dan diarahkan untuk mencapai manfaat umum. Pandangan ini menjadikan Bentham sebagai salah satu tokoh awal dalam aliran positivisme hukum, yaitu pandangan yang memisahkan secara tegas antara hukum sebagaimana adanya (law as it is) dan hukum sebagaimana seharusnya (law as it ought to be).
Warisan intelektual dari Bentham dalam bidang hukum sangatlah berpengaruh, baik dalam teori ataupun praktik. Pemikirannya membuka jalan bagi perkembangan pendekatan hukum yang berbasis pada rasionalitas, efektivitas, dan kesejahteraan sosial. Di samping itu, prinsip-prinsip utilitarianisme yang ia gagas juga menjadi landasan bagi berbagai disiplin ilmu hukum kontemporer, seperti analisis ekonomi terhadap hukum (law and economics) serta formulasi kebijakan publik yang berbasis bukti dan konsekuensi.
Dengan demikian, Jeremy Bentham bukan hanya seorang teoritikus, tetapi juga seorang arsitek intelektual dari hukum modern yang berpijak pada nalar praktis dan nilai-nilai manfaat sosial. Pemikiran-pemikirannya tetap relevan dalam menjawab tantangan-tantangan hukum dan kebijakan publik di era kontemporer. (MM/GI)